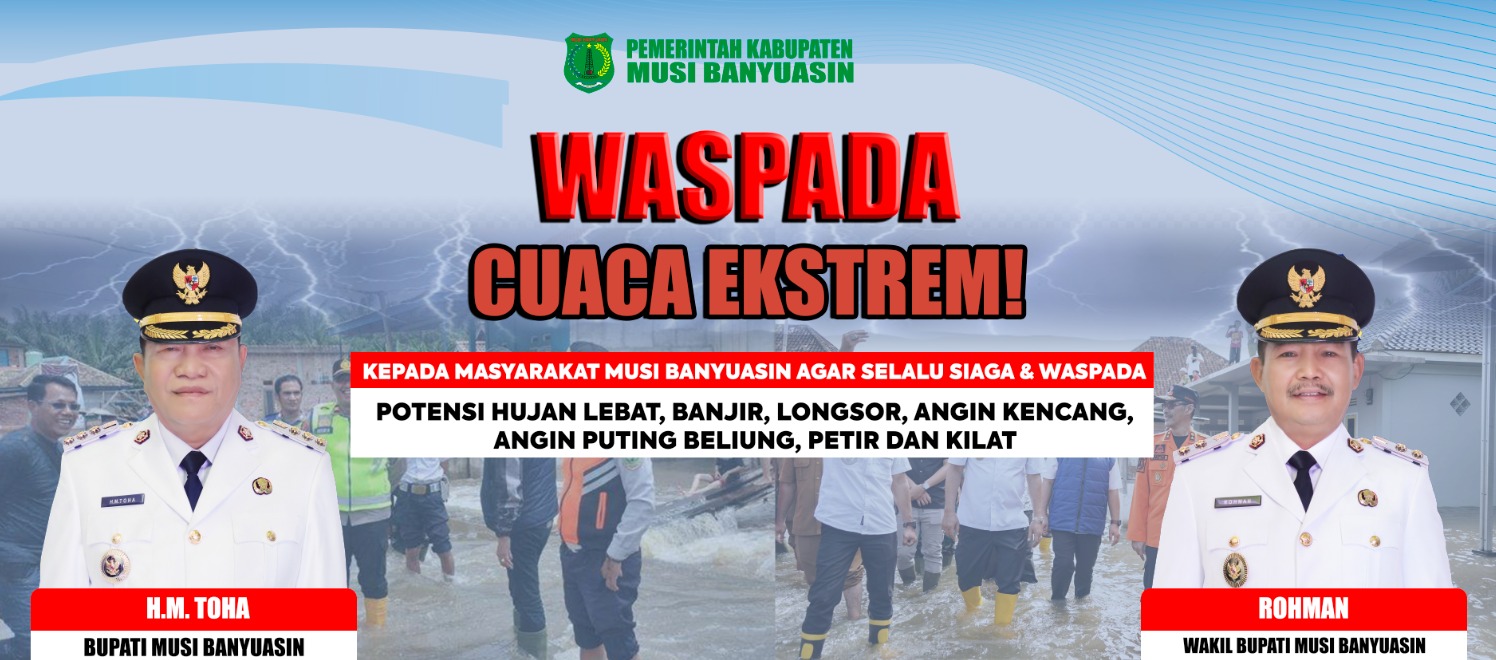Konsep Pendidikan Humanis
Paulo Freire menawarkan sebuah pendidikan alternatif atas konsep pendidikan yang monoton, searah dan tidak dialogis. Pemikiran yang lahir dari pergumulan selama bekerja di tengah-tengah masyarakat feodal yang hirarkis. Dalam pandangannya, pendidikan seperti itu hanya menempatkan peserta didik sebagai objek pasif yang semata-mata dituntut untuk menerima pengetahuan yang diberikan oleh orang lain kepadanya. Proses pembelajaran terpusat kepada pendidik sebagai satu-satunya pihak yang dianggap berpengetahuan sehingga cenderung searah yang mengakibatkan hilangnya kreatifitas peserta didik. Freire menyebut pendidikan seperti ini sebagai – Pendidikan Gaya Bank – lantaran peserta didik diilustrasikan mirip “tabung kosong” yang patut diisi dengan beragam pengetahuan sampai penuh. Berdasarkan lanskap realitas tersebut, Freire menawarkan konsep pendidikan yang secara substansial sangat berbeda, yaitu paradigma pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif, yang disebutnya sebagai Pendidikan Humanis.
Ada beberapa konsep penting untuk menguatkan gagasan pendidikan humanis yang ditawarkannya. Pertama, konsep manusia. Manusia merupakan makhluk unik dengan segala ciri khas yang dimilikinya sebagai pembeda dengan makhluk lainnya. Menurut Freire (2016), secara ontologis manusia berada dalam posisi sebagai subjek aktif yang bertindak terhadap dunia sekaligus mampu mengubah dunia tersebut. Dunia bagi manusia sebagai bagian luar dirinya sehingga ia menjadi sebuah tantangan untuk mengaktualisasikan diri, mengembangkan bakat minat yang ada pada dirinya untuk menciptakan hal baru yang bermanfaat bagi dirinya maupun manusia lainnya. Manusia merupakan makhluk yang hidup berdampingan dengan alam yang sejatinya menghadapi dunia sebagai realitas objektif. Pasalnya, manusia dan dunia saling berinteraksi sehingga manusia diperhadapkan dengan tantangan alam yang menuntutnya perlu kritis dan secara sadar merespons tantangan tersebut dengan reaksi yang paling rasional. Keputusan ini diambil berdasarkan refleksi seraya mengumpulkan data-data objektif menyangkut alam yang membatasi dirinya.
Dalam rangka mempertahankan hidup, manusia seyogianya meminimalisir ketergantungan penuh dengan alam. Artinya manusia perlu memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk memberikan reaksi berdasarkan refleksi terhadap alam. Oleh karena itu, Freire (2001) membedakan antara adaptasi dan integrasi untuk menyikapi alam sebagai tempat manusia melangsungkan kehidupan. Adaptasi di sini, sebagai bentuk pertahanan terhadap alam dengan menyesuaikan diri dengan realitas. Sementara integrasi merujuk kemampuan manusia melangsungkan hidup dengan mengubah realitas berdasarkan kondisi dan kebutuhannya. Dengan begitu, manusia dapat menentukan pilihan yang paling rasional dan masuk akal untuk diterapkan dalam kehidupannya.
Tidak sampai di situ, Freire bahkan memandang manusia sebagai makhluk yang dapat menangkap spirit zamannya. Manusia yang bergerak dinamis selalu menciptakan sesuatu yang baru dan dengan kekuatan pemikirannya manusia dapat menangkap historisitas atas sesuatu yang terjadi pada masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang. Hal ini sebagaimana penegasan Freire (2001) bahwa: “Untuk mengatasi dimensi tunggal, manusia mampu menjangkau hari kemarin, mengenai hari ini dan menemukan hari esok. Dan dimensi waktu adalah suatu penemuan yang sangat mendasar dalam sejarah kebudayaan manusia. Manusia berada dalam waktu. Mereka ada di dalam, di luar, mewarisi, melibatkan dan mengubah. Manusia tidak terpenjara dalam “hari ini” yang permanen, melainkan hadir dan menjadi temporal. Manusia hadir dari waktu, menyadari temporalitas, membebaskan diri dari “hari ini”, dan hubungannya dengan dunia menjadi penuh dengan konsekuensi. Peranan manusia dalam dan dengan dunia bukanlah peran yang pasif.”
Kedua, konsep pendidikan pembebasan. Keprihatinan manusia terhadap masalah humanisasi akan membawa pada pengakuan akan adanya dehumanisasi yang melekat dan semakin akut dengan kehidupan manusia. Hal tersebut terlihat dari ketidakadilan dan ketimpangan yang dirasakan oleh manusia yang tersisihkan. Selaras ditegaskan Feire (2016) bahwa: “Tetapi sepanjang humanisasi ataupun dehumanisasi merupakan pilihan-pilihan yang nyata, maka hanya yang pertama itulah yang merupakan fitrah manusia. Fitrah inilah yang senantiasa diingkari, namun demikian dia justru diakui melalui pengingkaran tersebut. Dia dimungkiri lewat perlakuan tidak adil, pemerasan, penindasan, dan kekejaman kaum penindas; dia diakui oleh adanya kerinduan kaum tertindas akan kebebasan dan keadilan, serta oleh perjuangan mereka untuk menemukan kembali harkat kemanusiaan mereka yang hilang.”
Freire (2016) menolak keras sikap fatalisme yang menempatkan manusia pada takdir yang hanya dapat diterima dan mutlak tidak dapat diubah. Maka diperlukan alat yang dapat melihat berbagai problem serta akar penyebabnya. Pendidikan yang memberikan wawasan dan pengetahuan kritis merupakan alat yang terbaik. Dalam hal inilah, pendidikan berperan sebagai jembatan pembuka gerbang kesadaran kritis. Tidak hanya mencapai kesadaran kritis namun juga diekspektasikan melangkah menuju upaya pembebasan yang mengantar peserta didik pada langkah konkret untuk mengubah situasi yang selama ini telah mengekang. Dengan begitu, jalan perjuangan akan ditempuh guna mendapatkan kebebasan demi merengkuh harkat kemanusiaan yang seutuhnya. Oleh karenanya, pendidikan memainkan peran penting humanisasi dengan bergerak bersama kaum tertindas untuk mengubah realitas penindasan menjadi suatu tatanan yang lebih adil dan lebih manusiawi.
Ketiga, konsep penyadaran. Menurut Freire (2016), manusia mempunyai kemampuan untuk mengetahui sesuatu karena dianugerahi akal oleh Tuhan. Hal ini memunculkan keyakinan tidak ada manusia yang bodoh. Dengan kemampuan untuk berpikir, maka manusia dapat memahami dan sadar akan berbagai realitas di sekelilingnya. Manusia menangkap realitas tersebut dalam hubungan kausalitas. Semakin manusia cermat mengamati dan memahami berbagai realitas di sekelilingnya maka ia semakin kritis. Begitu pula sebaliknya, jika manusia tidak dapat memahami realitas tersebut secara rasional maka ia akan cenderung terjebak dalam pemahaman yang bersifat magis dan mistis.
Guna mencapai tujuan penyadaran kritis dan menyeluruh, Freire (2001) mengajukan program pendidikan yang menyangkut konsep antropologis mengenai kebudayaan; yaitu pembedaan antara dunia natural dan dunia kultural, peranan aktif manusia dalam dan bersama dengan realitasnya, kebudayaan sebagai hasil kerja manusia (hasil kegiatan yang terus menerus berkelanjutan dengan mencipta dan mencipta kembali), makna transendental dari hubungan manusiawi, dimensi manusiawi dari kebudayaan; kebudayaan sebagai pencapaian sistematis dalam pengalaman manusia (tidak hanya sebagai tindakan menyimpan informasi, melainkan sebagai tindakan
kreatif), demokratisasi kebudayaan, membaca dan menulis sebagai kunci untuk memasuki ruang komunikasi tertulis.” Berangkat dari pemahaman di atas, maka manusia sebagai subjek aktif perubahan dengan mencipta dan terus mencipta kembali serta hadir dalam sejarah yang terus berlanjut.
Keempat, konsep pendidikan hadap masalah. Freire (2016) dengan keras mengkritik pola pendidikan yang memosisikan peserta didik sebagai objek. Ia menyebut pola pendidikan konservatif tersebut sebagai “Pendidikan Gaya Bank”. Dalam upaya melakukan kritik atas sistem tersebut ia kemudian mengemukakan konsep pendidikan yang disebut “Pendidikan Hadap Masalah”. Dalam konsep pendidikan hadap masalah, peserta didik diberikan keleluasaan untuk mencari dan menggali serta menemukan pengetahuan. Peserta didik diajak mengamati realitas sekelilingnya dan diberi kebebasan berpikir serta berusaha mencari dan menemukan sebab akibat yang menyangkut realitas dan permasalahannya. Dengan demikian, hal ini akan mengantar manusia ke jalur lebih manusiawi sehingga kemampuan berpikir kritisnya akan mulai terbangun dengan menemukan masalah dan akar masalah tersebut.
Kelima, konsep pendidikan dialogis. Konsep pendidikan hadap masalah bisa menjadikan pendidik dan peserta didik sebagai subjek yang berperan sama. Keduanya dihadapkan untuk media dalam membangun pengetahuan dan kesadaran pada realitas. Menurut Supriyanto (2013), implementasi teori eksistensi dalam pendidikan adalah tindakan anti dialogis. Freire mengemukakan pendidikan hadap masalah sebagai alternatif dengan menempatkan dialog sebagai sarana interaksi terbuka dalam membangun pengetahuan dan kesadaran. Dialog di sini tidak sekadar kata kosong tanpa makna, akan tetapi dialog sebagai suatu totalitas dialektis antara refleksi dan aksi yang melahirkan praksis pembebasan dalam tujuan mengubah dunia yang membelenggu kehidupan manusia.
Freire berpendapat, bahwa rasa cinta yang mendalam atas dunia sekaligus terhadap sesama manusia merupakan dasar dari sebuah dialog. Freire (2016) bahkan dengan tegas menjelaskan: “Sebagai sebuah bentuk laku keberanian, cinta tidak boleh menjadi sentimental, sebagai sebuah laku kebebasan, dia juga tidak boleh dijadikan alat untuk memanipulasi. Cinta harus melahirkan tindakan-tindakan pembebasan berikutnya; jika tidak dia bukan cinta…Jika saya tidak mencinta dunia–jika saya tidak mencintai kehidupan–jika saya tidak mencintai sesama–saya tidak dapat memasuki dialog.” Melalui dialoglah dimensi perjuangan menuju humanisasi akan terbuka yang tidak dibangun dalam relasi dominasi dengan tujuan untuk menguasai. Pun, tidak dibangun berdasarkan relasi vertikal dan patrimonial. (bersambung)
Penulis adalah ASN Lingkup Pemkab Lombok Utara dan Pengurus DPP Iprahumas Indonesia